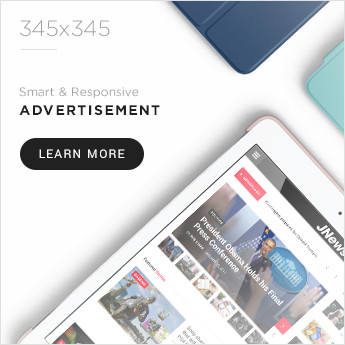Oleh: Soni Samoe
(Pendiri LSM LABRAK – Lembaga Aksi Bela Rakyat)
Pohuwato: 18 Agustus 2025
Gorontalo, KABARsindikat.ID –Isu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato sejatinya bukanlah perkara baru. Jika menggunakan istilah medis, maka PETI dapat dianalogikan sebagai penyakit kronis stadium lanjut yang sudah lama dibiarkan tanpa penanganan preventif. Ironisnya, kepanikan baru muncul ketika dampak lingkungan telah mencapai titik akut. Pertanyaan mendasarnya: di mana para pemangku kepentingan selama ini?
Sejak 2013, saya telah berulang kali mengingatkan bahaya laten PETI. Forum resmi, diskusi publik, hingga aksi demonstrasi telah saya tempuh sebagai jalan peringatan. Tanda-tanda kerusakan ekosistem sesungguhnya sudah sangat kasat mata, tetapi alarm peringatan itu seakan tidak pernah terdengar. Kini, ketika alam hampir sampai pada titik “breakdown,” barulah semua pihak berpura-pura tersentak dari tidur panjangnya.
Lebih ironis lagi, konstruksi narasi yang dibangun di ruang publik cenderung menyalahkan satu pihak saja: pelaku PETI lokal. Padahal, ini jelas reduksionis dan menutup mata dari kenyataan struktural yang lebih besar. Apakah kita pura-pura tidak tahu bahwa perusahaan raksasa seperti PT Merdeka Cooper Gold hingga kini saja belum jelas status dokumen AMDAL-nya?
Arahkan pandangan ke Gunung Pani. Dari sudut mana pun di sekitar ibu kota Pohuwato, tampaklah luka terbuka: bukit yang semakin tandus, hutan yang tergerus, dan tanah yang rentan erosi. Aktivitas korporasi berskala besar jelas menyumbang sedimentasi masif di hilir. Maka, menyalahkan semata PETI rakyat tanpa menyentuh kontribusi korporasi adalah bentuk ketidakadilan epistemik sekaligus politik.
Lebih jauh, ada paradoks lain. Sebagian pelaku PETI lokal justru berupaya menunjukkan tanggung jawab moral—misalnya dengan membantu pengerukan sedimen demi kepentingan petani. Fakta ini membuktikan bahwa generalisasi bahwa “semua PETI perusak” adalah sesat pikir. Yang perlu ditegakkan adalah diferensiasi: siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang abai. Atensi hukum mesti diarahkan pada aktor-aktor PETI yang tidak peduli dampak ekologis, baik itu individu bermodal kecil maupun korporasi bermodal raksasa.
Namun, yang paling sering absen dalam diskursus ini adalah peran pemerintah daerah. Bagaimana mungkin solusi bisa diharapkan, jika Dokumen Jaminan Reklamasi Pasca Tambang—syarat utama terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR)—hingga kini tak jelas nasibnya? Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebenarnya sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Gorontalo Nomor 98 Tahun 2022, tetapi terlambat 13 tahun dibandingkan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) untuk korporasi besar sejak 2009.
Keterlambatan struktural inilah yang menciptakan ruang abu-abu hukum, sehingga masyarakat tambang terjebak dalam stigma “ilegal.” Mereka ibarat “anak tiri” di tanah sendiri: dipinggirkan regulasi, tapi diperas realitas ekonomi.
Dalam konteks ini, isu PETI seharusnya dibaca sebagai momentum untuk menata ulang regulasi. Alih-alih terus-menerus mengutuk, negara justru mestinya hadir dengan menuntaskan prasyarat administratif IPR, sehingga aktivitas rakyat tambang memiliki payung legal yang jelas. Tanpa itu, kita hanya melestarikan ketidakpastian, membiarkan konflik horizontal terus berulang, dan pada akhirnya merusak legitimasi negara di mata rakyat.
Media, wartawan, dan LSM memang konsisten menjadi garda depan mengawal isu ini. Namun, ironinya, suara-suara publik justru lebih sering diposisikan sebagai “gangguan” ketimbang sebagai instrumen koreksi kebijakan. Padahal, di dalam demokrasi, fungsi check and balance tidak hanya milik legislatif, tetapi juga publik sipil yang bersuara.
Oleh karena itu, antitesis dari situasi timpang ini adalah: menata ulang ekosistem pertambangan rakyat, menghadirkan keadilan ekologis sekaligus keadilan sosial. Pemerintah daerah mesti segera menuntaskan dokumen prasyarat IPR, sementara aparat hukum harus objektif menindak aktor-aktor perusak lingkungan, tanpa pandang bulu. Korporasi besar pun tidak boleh lagi berlindung di balik jargon investasi sambil mengabaikan kewajiban AMDAL.
Jangan biarkan rakyat termarginalisasi di tanah kelahirannya sendiri. Jangan pula biarkan korporasi transnasional mendapatkan karpet merah tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, isu PETI bukan sekadar problem ekonomi rakyat, melainkan juga persoalan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan bahkan kredibilitas negara. Jika kita masih terus melihat masalah ini dengan kacamata sempit, maka benar adanya, bangsa ini akan terus mengulangi kesalahan yang sama: mengobati penyakit setelah kronis, alih-alih mencegah sejak dini.
Tim-Redaksi